Apakah Kamu Melakukan Toxic Positivity? Begini Cara Mengeceknya
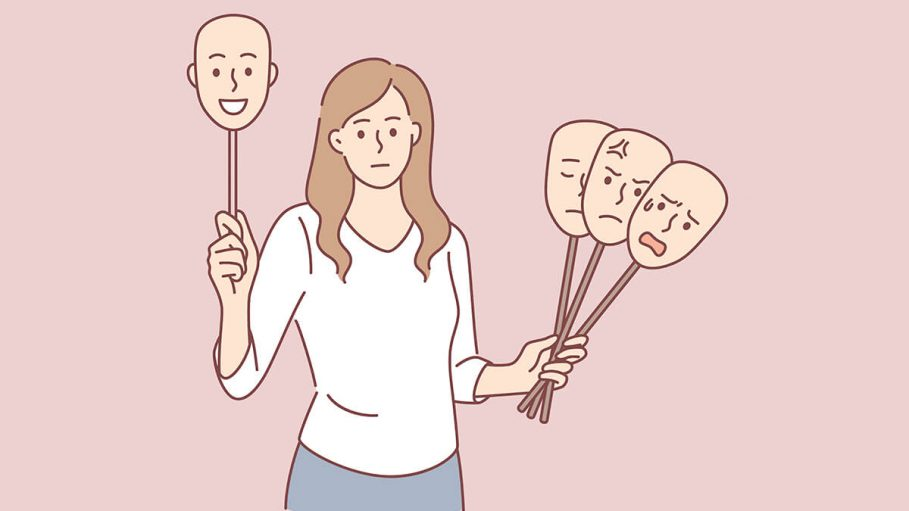
Ah, toxic positivity —kamu berkali-kali mendengar tentang hal ini di percakapan teman dan media sosial. Bahkan mungkin terlibat secara emosi dan intens saat membaca sebuah utasan di Twitter tentang sesuatu yang sepertinya positif, tapi juga terkesan negatif ini. Seandainya kamu masih bingung dengan artinya, menurut psikolog Amerika, Konstantin Lukin, toxic positivity adalah adanya fokus dan obsesi berlebihan pada hal-hal positif sehingga kita menolak apa pun yang dapat memicu emosi atau perasaan negatif.
Efeknya? “Ketika kita menyangkal atau menghindari emosi yang tidak menyenangkan, kita membuat intensitas emosi tersebut menjadi lebih besar. Ketika kita terjebak dalam siklus ini, emosi ini menjadi lebih berat untuk dikelola. Sehingga, emosi tersebut tidak berhasil diproses dengan efektif, melainkan hanyalah dipendam atau diabaikan saja,” jelas Sarahsita Hendrianti, M.Psi., Psikolog, seorang psikolog klinis dewasa dari Pion Clinician, Cilandak, Jakarta Selatan, kepada LIMONE.
Ingin tahu lebih jelas tentang efek toxic positivity bagi kehidupan sehari, dan bagaimana menjadi positif, tapi tidak toxic? Baca artikel ini sampai habis.
Daftar Isi
1 Bagaimana Toxic Positivity Bisa Terjadi?
2 Apa Tanda-Tanda Toxic Positivity?
3 Apa Dampak Sikap Positif yang Toxic Ini?
4 Bagaimana Jika Toxic Positivity Dibarengi Niat Baik?
5 Bagaimana Membedakan Positif yang Sehat dengan Toxic Positivity?
6 Bagaimana Mengurangi Sikap Positif yang Toxic Ini?
Bagaimana Toxic Positivity Bisa Terjadi?

Jika kamu pernah mendengar pernyataan seperti “kamu harus bersabar setiap saat… ” atau “positive vibes only…”, atau “berbahagialah setiap saat,”—breakingnews: ini adalah sejumlah contoh toxic positif.
“Secara superficial, pernyataan tersebut tentu saja terdengar menyenangkan, namun pada hakikatnya seseorang hanya bisa berkembang dan menjadi dewasa dan matang dari pengalaman-pengalaman subjektif, yang mungkin sebagian besarnya adalah pengalaman atau emosi yang tidak menyenangkan,” terang Sarahsita.
“Seseorang akan belajar memaknai, menghargai hidupnya dengan mendalam dari kesalahan serta perasaan yang tidak menyenangkan,” tambahnya.
Dengan kata lain, adalah sesuatu yang normal jika kita merasa kecewa, sedih dan marah saat gagal—jadi, tidak perlu ditekan atau dihapus.
Mengapa kita mengucapkan hal-hal yang adalah toxic positivity (mungkin secara tidak sadar)?
“Hal ini biasanya disebabkan karena kita sering merasa tidak berdaya atau tidak nyaman ketika berhadapan dengan rasa sakit serta emosi negatif orang lain. Tanpa kita sadari, kita ingin mem-block emosi negatif tersebut,” jelasnya.
Padahal, super penting untuk diingat: Seberat apapun kita menyaksikan seseorang yang sedang bersedih, penting untuk tidak ‘menggagalkan’ perasaan mereka dengan sikap (toxic) positive.
“Perilaku yang jauh lebih bermanfaat dan valid adalah mendengarkan mereka, dengan niat yang tulus untuk memahami, bukan semata-mata untuk memecahkan masalah saja. Biarkan orang itu tahu bahwa tidak apa-apa bagi mereka untuk merasakan apapun yang mereka rasakan,” tegasnya.
Mengutip sebuah mantra yang sering diulang-ulang di masa pandemik ini (dan kebetulan menjadi drama Korea yang sedang heboh): it’s okay to be not okay.
Dan menurut Sarahsita, ada kekeliruan persepsi tentang toxic positivity ini. “Positivity dianggap sebagai ‘obat’ yang mujarab untuk segala permasalahan hidup. Padahal, tidak selalu demikian. Menghindari emosi negatif hanya akan menunda proses pengolahan emosi itu sendiri. Ketika yang kita hadapi adalah pengalaman traumatis, toxic positivity hanya akan menunda pemulihan kita pasca kejadian traumatis tersebut,” dia mengingatkan.
Apa Tanda-Tanda Toxic Positivity?

Mungkin awalnya sulit dideteksi, terutama jika toxic positivity seperti menjadi kode etik percakapan di sekitarmu. Namun, dari sekarang, kamu bisa mengetahuinya dengan memperhatikan beberapa perilaku dan ekspresi umum di bawah ini. Menurut Sarahsita, toxic positivity adalah cenderung:
- Menyembunyikan/ menutupi/ menyangkal perasaanmu yang sebenarnya.
- Mencoba “move on” dengan menjejali diri dengan hal-hal yang positif.
- Berusaha untuk mengalihkan/ memendam/ ‘menghilangkan’ emosi atau perasaan yang tidak menyenangkan.
- Merasa bersalah karena merasakan apa yang kita sedang rasakan. Misalnya, malu karena menangis, merasa cengeng, menganggap diri ‘baperan’ karena tersinggung dengan ucapan teman yang menyakiti.
- Meminimalisir/ mengurangi/ menggagalkan emosi atau perasaan negatif orang lain dengan kalimat dukungan seperti, “jangan sedih…”, “ayo semangat…”, atau “nggak boleh nangis…”
- Mencoba memberikan perspektif kepada seseorang. Misalnya dengan mengatakan, “untung saja kamu tidak mati”, atau “kamu harus bersyukur karena masih punya pekerjaan”—alih-alih memvalidasi pengalaman emosional mereka.
- Mempermalukan atau menghukum orang lain karena mengekspresikan emosi negatif mereka, misalnya dengan bilang, “ah cengeng kamu! atau, “gimana, sih? Masa cowok nangis?”
Apa Dampak Sikap Positif yang Toxic Ini?

Sarahsita menegaskan bahwa dengan menghindari emosi atau perasaan negatif, bisa menyebabkan kita akan mungkin kehilangan informasi berharga.
Contoh dalam kehidupan sehari-hari: ketika kita sedang merasa takut, berarti saat itu emosi kita hendak memberi tahu kita untuk waspada, bahwa ada sesuatu yang mengancam akan terjadi. Dengan kata lain, “emosi itu sendiri pada dasarnya adalah sebuah informasi dan memberikan gambaran tentang apa yang terjadi pada saat tertentu,” jelasnya.
Walaupun demikian, penting diingat bahwa emosi-emosi kita tersebut bukan menjadi kendali utama kita dalam melakukan hal tertentu.
“Misalnya, jika saya takut pada seekor anjing dan saya melihat seekor anjing di depan di trotoar, itu tidak berarti saya harus menyeberang jalan atau berlari. Melainkan hanya berarti bahwa saya menganggap anjing sebagai potensi ancaman,” ujarnya memberikan contoh.
Entah memilih untuk berlari atau tetap berjalan melewati anjing tersebut, “sepenuhnya ada di bawah keputusan saya. Intinya, ketika seseorang mengidentifikasi emosi, dia sendiri yang memutuskan apakah ia ingin menghindari ancaman tersebut, atau menghadapinya,” imbuhnya.
Perasaan pada anjing—atau pada hal lain—tersebut, tidak perlu disangkal. Pasalnya, dengan menyangkal emosi dan perasaan kita, kita seperti sedang menyangkal sebuah kebenaran serta kejujuran diri.
“Kita kehilangan koneksi dengan diri kita sendiri, sehingga sulit bagi orang lain untuk terhubung dan berhubungan dengan kita. Kita mungkin terlihat kuat dari luar, tetapi di dalam diri kita penuh dengan rasa takut, rasa terancam, bahkan rasa tidak puas dengan diri sendiri. Teman-teman kita mungkin menjadi tidak nyaman untuk mencurahkan isi hatinya, mengutarakan tentang pengalaman gelapnya secara mendalam,” tambahnya.
Bagaimana Jika Toxic Positivity Dibarengi Niat Baik?

“Meskipun niat kita baik, tetapi pada kenyataannya, secara tidak sadar kita mengirimkan pesan kepada mereka bahwa, ‘saya hanya mengizinkan kamu untuk membagi perasaan yang baik-baik saja,’” ujarnya.
Akibatnya, seperti yang sudah disinggung di atas, orang lain akan sangat sulit untuk mengekspresikan apapun selain “positive vibes” ketika mereka sedang bersama kita. Otomatis, kemungkinan besar orang lain itu akan mengikuti ‘aturan’ yang kita terapkan, yakni dilarang menjadi diri sendiri.
Jika toxic positivity dijadikan pedoman hidup, “konsekuensi jangka panjangnya adalah kita akan sulit untuk menjalin hubungan yang suportif dan hangat dengan orang lain. Kita akan sulit untuk membangun percakapan yang intim dengan orang lain,” paparnya.
Sarahsita menyinggung bahwa hubungan dengan diri sendiri, seringkali tercermin dalam hubungan yang kita jalin dengan orang lain.
Maksudnya?
“Jika kita tidak bisa jujur tentang perasaan kita sendiri, bagaimana kita bisa memberikan ruang bagi orang lain untuk mengungkapkan perasaan mereka di hadapan kita? Dengan menciptakan ‘dunia’ emosional ‘palsu’, kita seperti menarik lebih banyak kepalsuan yang kemudian akan menghasilkan keintiman ‘palsu’ dan persahabatan yang dangkal,” ujarnya.
Bagaimana Membedakan Positif yang Sehat dengan Toxic Positivity?

Ini bukan berarti kamu dilarang untuk menjadi positif. Namun, memang ada perbedaan antara positif yang sehat dengan toxic positivity yang cenderung negatif.
“Cara membedakan yang paling mudah adalah dengan menjadi individu yang realistis,” tuturnya.
“Realistis berarti kita menyadari bahwa setiap hal yang kita alami pastinya memiliki dua sisi, positif dan negatif. Kita tidak perlu melihat dunia melalui kacamata positif setiap saat, tetapi bangun rasa percaya bahwa menikmati hal-hal kecil dalam hidup memudahkan kita untuk melewati hal-hal buruk,” ujarnya.
Sebuah penelitian terbaru mendukung hal ini, bahwa sikap realistis adalah cara terbaik menghadapi hidup. Bukan terlalu optimis atau pesimis.
“Penting diingat bahwa tidak semua hal atau perasaan negatif yang kita alami dan rasakan murni karena kesalahan kita saja. Maka dari itu, kita punya hak untuk meminta dukungan, baik berupa solusi maupun dukungan emosi,” tambahnya.
Jadi, apakah terkadang kamu merasa hidupmu terasa menyebalkan? Itu hal yang alami. “Kita tidak perlu bahagia, ceria setiap detik setiap hari. Adalah hal yang manusiawi dan normal untuk mengalami rasa menderita, terluka, merasa marah dan kecewa. Mengakui, menerima emosi negatif jauh lebih bermanfaat daripada menyangkalnya,” tegasnya.
Bagaimana Mengurangi Sikap Positif yang Toxic Ini?

Bukan bermaksud untuk bersikap toxic positivity, tapi kabar baiknya: ada cara-cara yang bisa kamu lakukan untuk mengurangi perilaku ini demi menyeimbangkan hidup.
Untuk diri sendiri:
- Hindari mengusir perasaan negatif
Merasa sedih, marah, frustrasi dan putus asa ketika kesulitan melanda adalah hal yang sangat manusiawi. “Seperti yang sudah dijelaskan, menghindari emosi yang menyakitkan akan membuat emosi tersebut semakin berat untuk dikelola. Hal yang terpenting adalah adanya keseimbangan antara emosi negatif dan positif yang sudah diperhitungkan dengan matang. Triknya adalah dengan menghadapinya dengan lebih efektif, sehingga kamu tidak terjebak dalam spiral negatif,” saran Sarahsita.
- Pelajari perbedaan antara hal-hal yang dapat dan tidak dapat kamu ubah
Bangun keberanian dan keterampilan memecahkan masalah, buatlah daftar solusi yang mungkin bisa diambil dan mulailah mengerjakannya. “Tetapi perlu dipahami bahwa tidak setiap masalah dapat diselesaikan dalam semalam. Mempelajari cara menerima hal-hal yang tidak dapat kita ubah bukanlah proses yang mudah atau cepat,” dia mengingatkan.
- Identifikasi dan koreksi kesalahan berpikir kamu
Seandainya kamu perlu diingatkan: sangat normal untuk memiliki pikiran negatif sesekali, “tetapi kadang-kadang, pikiran negatif tersebut tidak bisa memberikan sesuatu yang positif pada diri kita,” jelasnya.
Apakah kamu penganut paham half-glass empty dan selalu memikirkan skenario terburuk ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana (worst case scenario)? “Kritisi dulu, apakah yang kamu pikirkan sesuai dengan kenyataannya? Apakah hal tersebut bisa membuatmu lebih antisipatif, atau justru malah memperparah rasa takutmu?” tegasnya.
- Bangun jarak aman dengan penganut toxic positivity
“Ketika kita mendapati teman atau keluarga kita memiliki sikap tersebut, bangun jarak (boundaries) yang aman agar toxic positivity tersebut tidak menghambat proses pengembangan diri kamu secara keseluruhan,” sarannya.
Dan ketika kamu merasa kurang didengar dan dipahami oleh keluarga dan teman-temanmu, cobalah untuk mengekspresikan emosimu dengan cara yang konstruktif.
Oh, satu lagi yang tidak kalah penting: “Cari bantuan profesional jika kamu membutuhkannya,” katanya.
Untuk hubungan dengan orang lain:
Tidak hanya terhadap diri sendiri, kamu juga bisa mulai mengurangi kebiasaan toxic positivity ini.
Caranya?
“Ketika orang yang kita cintai mencurahkan perasaan mereka, yang perlu diingat adalah bahwa perasaan mereka tersebut adalah nyata. Normal bagi mereka untuk merasa sedih, marah, frustrasi dan tidak berdaya,” katanya.
Dan mungkin kmau sudah sering mendengar bahwa, terkadang teman atau orang lain curhat karena mereka hanya ingin didengar dan dipahami.
Sama seperti dengan yang sering kamu alami dan rasakan, seseorang ingin membicarakan masalah mereka karena hal tersebut akan membantu menjernihkan dan meluruskan pikiran mereka. Jadi, dengarkan mereka.
“Dukungan kamu akan mendorong mereka untuk menjadi kuat dalam mengatasi masalah mereka, bahkan ketika kamu tidak memberikan ceramah apapun kepada mereka. Tahan diri untuk memberikan saran atau menawarkan kiat —kecuali temanmu secara khusus memang memintanya,” sarannya.
Bingung harus mengatakan apa? Menurut Sarahshita, berikut adalah beberapa ungkapan yang bisa kamu katakan.
- “Aku ikut berempati mendengar apa yang sedang kamu alami. Apa yang bisa kubantu?”
- “Aku tahu kamu sedang mengalami masa-masa sulit. Tapi aku juga tahu kamu kuat.”
- “Wajar banget kalau kamu merasa kewalahan dan bingung dalam situasimu saat ini.”
- “Aku tidak tahu harus berkata apa, tapi aku di sini untukmu, ya.”
- “Berat rasanya, ya. Adakah yang bisa kamu lakukan hari ini untuk membuatmu merasa sedikit lebih baik?”
- “Kamu tidak salah jika merasa marah, dan tidak ada yang menyalahkanmu.”
- “Saya tahu ini sulit, tetapi kamu sudah melakukan hal yang efektif dalam menangani ini.”
- “Wah, itu pasti menyebalkan banget, ya. Apa yang aku bisa bantu?”
